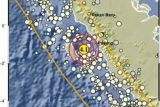Langit mulai diselimuti mendung ketika pompong yang merupakan sebutan masyarakat Mentawai untuk sebuah sampan kecil berkapasitas tujuh orang membelah Sungai Batnoinan Puro.
Di kemudi, Nikodemus Sabulukkungan, seorang pria paroh baya, tengah menuju lokasi tempat pengolahan sagu di kawasan Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.
Setelah merapat, di antara pepohonan sagu yang menjulang ia mulai menatak sebuah pohon sagu yang sudah tumbang. Dengan sebilah kapak, ia kemudian memisahkan antara kulit dan isi pohon yang sebelumnya sudah dibagi menjadi potongan sepanjang lebih kurang 70 centimeter.
Gerimis mulai turun ketika ia sibuk mempersiapkan sagu yang merupakan makanan pokok masyarakat Mentawai untuk kemudian diparut menggunakan parutan tradisional yang disebut dengan gagaji.
Setelah selesai diparut menggunakan alat tradisonal gagaji, sagu tersebut kemudian dibawa menuju dereat. Dereat adalah sebuah alat pengolahan lainnya untuk kemudian dipisahkan antara sari dan ampasnya.
Dereat sendiri terdiri atas beberapa bagian. Pada bagian paling atas terdapat sebuah wadah bersegi empat tempat memeras sagu menggunakan air yang disebut dengan karuk.
Menggunakan timba dengan bahan pelepah sagu, Nikodemus menimba air ke dalam karuk agar sari dari sagu ikut mengalir bersama air menuju ke saringan yang ada di bawahnya.
Tepat di bawah saringan terdapat dedeibu, sebuah wadah berupa sampan kecil menampung cucuran air disertai dengan sari dari parutan sagu yang sebelumnya sudah diperas.
Sembari tetap memeras sagu, ia menuturkan butuh waktu hingga dua jam agar sari pati sagu dapat benar-benar berpisah dengan air perasan, setelah itu baru didapatkan sagu yang siap untuk dikonsumsi.
Sagu tersebut kemudian akan disimpan pada sebuah wadah yang terbuat dari daun sagu berukuran panjang sekitar satu meter, dengan diameter sepanjang 25 centimeter yang disebut dengan tappri.
Vincent Sabulukkungan yang kala itu ikut membantu Nikodemus mengolah sagu menyebutkan, satu potongan sagu dapat mengisi penuh tappri untuk keperluan makan selama satu satu bulan bagi sebuah keluarga kecil yang terdiri dari orang tua dan satu anak.
Apabila untuk keperluan sehari-hari maka pekerjaan mengolah sagu akan dilakukan oleh anggota keluarga yang bersangkutan, sementara apabila sagu tersebut akan dipergunakan untuk keperluan upacara adat, maka yang akan bekerja adalah kaum laki-laki dari suku yang bersangkutan.
Menurutnya selama ini belum pernah ada orang Mentawai yang kelaparan dan kekurangan makanan, sebab segala kebutuhan sudah disediakan oleh alam, seperti sagu yang tumbuh subur dan melimpah ruah di sekitar mereka.
Bukannya tidak pernah memakan nasi, Vincent menambahkan bahwa rata-rata orang Mentawai sudah terbiasa mengonsumsi sagu, bahkan bagi mereka sagu lebih tahan lama di perut dari pada nasi.
Sementara Nikodemus sibuk mengolah sagu, Agustinus Durai yang juga ikut dalam pengolahan menambahkan, tidak semua sagu dapat diolah. Ada batasan-batasan umur tertentu agar sagu dapat ditebang untuk kemudian dijadikan tepung sagu.
Setidaknya sagu harus berumur 17 tahun agar pohonnya benar-benar berisi untuk dapat diolah, sebab pada umumnya batang sagu yang usianya di bawah batasan tersebut belum terlalu berisi dan masih lunak untuk dapat diparut dan diolah.
Ia menuturkan setelah pohon sagu pada sebuah kawasan mulai berkurang, maka secara otomatis masyarakat akan langsung menanam penggantinya sehingga persedian sagu akan selalu ada untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Nikodemus hampir selesai memeras parutan sagu ketika Agustinus menyebutkan bahwa sagu yang sudah diolah dapat bertahan dengan pengawetan alami.
Sagu yang sudah disimpan di dalam tappri dan direndam dalam air dapat bertahan hingga satu tahun, sehingga masyarakat tidak perlu pusing memikirkan persediaan makanan.
Agustinus menekankan bahwa kehidupan masyarakat Mentawai sangat bergantung pada alam. Apabila alam mulai rusak dan tumbuhan sagu mulai menipis maka masyarakat akan mulai kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan.
Untuk dapat dikonsumsi, sagu yang sudah diolah menjadi tepung harus dimasak terlebih dahulu dan dimasaknya juga memanfaatkan hasil alam.
Memasak Sagu
Seusai mengolah sagu, Nikodemus, Agustinus dan Vincent kembali mengarahkan pompong miliknya kembali menuju Uma Sabulukkungan, rumah adat khas Mentawai kepunyaan Suku Sabulukkungan.
Di dapur, tepat pada bagian belakang uma, beberapa orang wanita sibuk menyiapkan beberapa bahan yang akan diolah. Selain sagu, di sekitar perapian atau tungku beberapa batang bambu yang sudah dipotong-potong disandarkan untuk nantinya digunakan sebagai wadah dalam memasak sagu.
Sembari menghaluskan tepung sagu yang akan dimasak, Lidiana Sabulukkungan, wanita yang tepat berumur setengah abad itu menceritakan bahwa hingga saat ini masyarakat Mentawai masih memasak sagu menggunakan cara yang tradisional, yaitu memanggang sagu di dalam bambu.
Setelah mulai halus, Lidia kemudian memasukkan sagu ke dalam potongan-potongan bambu untuk kemudian disangai di sekitar api yang sudah dinyalakannya di dalam tungku.
Tidak kurang dari 15 batang bambu berisi sagu berjejer menghadap api, ketika satu sisi bambu mulai berubah warna, maka Lidia akan segera memutarnya sehingga panas api dapat memasak sagu secara merata. Sagu yang dimasak dengan cara ini disebut dengan sagu kaobbuk.
30 menit berlalu ketika seluruh bagian bambu mulai berubah warna kehitaman yang menandakan sagu mulai masak sempurna, sambil mengganti sagu yang sudah masak tersebut dengan sagu lainnya, ia menyebutkan bahwa sagu tidak hanya dapat diolah dengan cara tesebut.
Sagu kapurut, tidak jauh berbeda dengan sagu kaobbuk. Sagu ini tetap dimasak dengan cara dipanggang, akan tetapi tidak lagi menggunakan bambu melainkan daun sagu.
Lebih lanjut wanita yang sudah mulai berumur tersebut menjelaskan bahwa dalam memasak sagu api yang digunakan tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil.
Jika api yang digunakan terlalu besar maka sagu tidak akan matang dengan sempurna, hanya bagian luarnya saja, sementara bagian dalamnya masih mentah. Selain itu jika api yang digunakan terlalu besar sagu juga bisa berubah rasa menjadi pahit.
Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu gampang, begitulah Lidia menjelaskan bagaimana cara memasak sagu. Untuk menambah cita rasa, sagu yang dimasak bisa saja ditambah dengan menggunakan parutan kelapa atau gula.
Lidia kemudian mencicipi sagu kapurut yang sudah matang, setelah dua kunyahan dia bergumam bahwa sagu yang sudah masak ini nanti akan lebih nikmat jika dikonsumsi dengan campuran ikan atau pun sayur-sayuran yang diambil dari ladang.
"Kami belum pernah merasa kekurangan bahan makanan, sebab apa yang kami konsumsi sudah disediakan oleh alam," tambahnya sembari melahap sagu yang telah dimasaknya itu. (*)